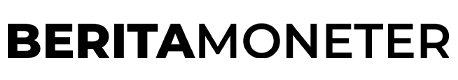Sementara di sudut-sudut negeri, di luar radar hiruk pikuk media, masih banyak anak-anak yang harus berjalan belasan kilometer untuk bersekolah.
Mereka tidak tahu apa itu demokrasi digital, tidak peduli siapa yang menang debat di televisi.
Mereka hanya tahu satu hal: hak mereka untuk belajar belum dijamin negara.
Data Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur mencatat masih ada lebih dari seribu sekolah dasar yang jauh dari pemukiman warga, membuat ribuan anak menempuh perjalanan panjang setiap hari.
Di banyak tempat, sekolah tidak memiliki guru tetap, ruang kelas bocor, dan buku hanya tinggal simbol di rak.
Inilah paradoks paling getir dari demokrasi kita: kebebasan berbicara di kota besar tumbuh subur, tetapi hak-hak dasar di daerah terpencil masih layu.
Bagaimana mungkin kita menyebut diri demokratis jika kesetaraan akses terhadap pendidikan masih menjadi kemewahan?
Demokrasi seharusnya menjamin bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk maju.
Anak-anak di pedalaman yang berjalan puluhan kilometer untuk sekolah adalah cermin dari demokrasi yang gagal menyeimbangkan pusat dan pinggiran.
Kelemahan distribusi keadilan ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih berorientasi pada prosedur, bukan pada keadilan sosial.