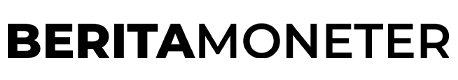JAKARTA – Seruan “Bubarkan DPR” mungkin terdengar radikal, bahkan mustahil secara hukum.
Namun, narasi ini bukan sekadar letupan emosional atau slogan jalanan.
Ia adalah puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap sistem politik yang semakin korup, ketika demokrasi direduksi menjadi pasar transaksi, dan parlemen kehilangan makna sejatinya sebagai rumah rakyat.
Hari ini, pemandangan aksi protes di depan Gedung DPR bukan lagi fenomena baru. Mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil silih berganti turun ke jalan menuntut akuntabilitas.
Mereka menolak rancangan undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik, mengecam kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi, hingga menggugat lemahnya pengawasan terhadap eksekutif.
Di mata rakyat, DPR telah bertransformasi menjadi lembaga yang sibuk mengurus diri sendiri ketimbang memperjuangkan kepentingan umum.
Politik Uang: Fondasi Busuk Parlemen
Bawaslu RI mencatat 130 kasus politik uang pada Pilkada 2024. Itu hanya data resmi, sekadar puncak gunung es.
Rakyat tahu, hampir setiap kursi DPR RI dimenangkan lewat praktik kotor: amplop yang dibagikan menjelang pencoblosan, paket sembako, hingga janji proyek yang memanipulasi kebutuhan masyarakat miskin.
Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, pernah membuka tabir gelap ini: modal untuk menjadi anggota DPR RI berkisar Rp5–15 miliar per orang.
Dan itu hanya ongkos pribadi. Partai politik harus mengucurkan dana jauh lebih besar untuk lolos parliamentary threshold sebesar 4%.
Hitungan sederhana menunjukkan partai butuh Rp180 miliar hanya untuk mengamankan 24 kursi, dengan rata-rata biaya Rp7,5 miliar per kursi.
Kalkulasi ini memberi pesan jelas: kursi parlemen bukan lagi ruang pengabdian, melainkan investasi politik. Para kandidat maju bukan untuk mengabdi, melainkan untuk balik modal.
Maka jangan heran, ketika isu kenaikan tunjangan DPR sebesar Rp50 juta mencuat, publik bereaksi keras. Angka itu tampak kecil bila dibandingkan dengan modal politik besar yang mereka keluarkan.
Dan inilah masalah pokoknya: parlemen kita dipenuhi pedagang, bukan negarawan.
DPR: Perkasa di Atas Kertas, Rapuh di Hati Rakyat
Secara konstitusional, DPR adalah lembaga superkuat. Setelah amandemen UUD 1945, posisinya setara dengan presiden.
Tidak ada presiden lagi yang bisa membubarkan DPR, sebagaimana pernah dilakukan Soekarno pada 1960 atau dicoba Gus Dur pada 2001.
Namun, kekuatan formal itu tak sejalan dengan legitimasi moral. DPR kerap bungkam ketika koruptor mendapat remisi.
Mereka lemah dalam fungsi pengawasan, bahkan sering menjadikan legislasi sebagai komoditas barter politik.
Anggaran negara pun disandera oleh kepentingan jangka pendek, bukan visi jangka panjang.
Paradoks pun lahir: DPR yang begitu kuat di atas kertas, justru rapuh di hati rakyat.
Jalan Revolusioner: Bukan Senjata, Tapi Kesadaran Publik
Lalu apa jalan keluarnya?
Membubarkan DPR secara hukum nyaris mustahil. Aksi massa berjilid-jilid pun hanya akan dicap “premanisme” dan dibenturkan dengan aparat. Satu-satunya jalan revolusioner adalah menghantam logika politik uang.
Selama rakyat masih rela menjual suaranya dengan harga Rp50 ribu atau sekotak mie instan, kursi DPR akan terus dikuasai oleh mereka yang bermodal besar. Namun, jika rakyat kompak menolak dijadikan komoditas, sistem akan berubah.
Inilah revolusi kesadaran rakyat: