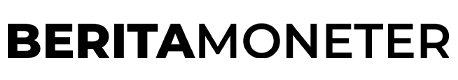JAKARTA – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, melontarkan kritik keras terhadap praktik rangkap jabatan yang melibatkan 30 wakil menteri di Indonesia.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga mencerminkan krisis etika di kalangan elite pemerintahan.
“Di negara demokrasi yang maju, rangkap jabatan dibatasi secara ketat karena dinilai dapat menumpuk kekuasaan dan menimbulkan konflik kepentingan. Tapi di Indonesia justru dibuka lebar. Ini bukan kemajuan, ini kemunduran,” ujar Hardjuno dalam pernyataan tertulisnya, Senin (14/7).
Ia menilai bahwa langkah sejumlah pihak yang menggugat aturan rangkap jabatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan sinyal penting bahwa publik tidak tinggal diam.
Gugatan tersebut, katanya, sudah cukup menjadi bukti adanya persoalan moral dalam tata kelola pemerintahan.
“Jika sebuah kebijakan sampai harus diuji di Mahkamah Konstitusi, itu artinya ada persoalan moral yang serius. Terlebih lagi ini menyangkut jabatan publik yang berkaitan langsung dengan kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Hardjuno menegaskan bahwa posisi menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan dalam struktur kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, jika menteri dilarang merangkap jabatan, maka prinsip yang sama juga harus diberlakukan kepada wakil menteri.
“Wakil menteri bukan pejabat independen. Ia adalah perpanjangan tangan dari menteri, bukan pemegang garis komando sendiri. Maka, bila menteri tidak boleh rangkap jabatan, wakilnya juga harus tunduk pada prinsip yang sama,” jelasnya.
Ia mengacu pada sejumlah aturan perundang-undangan yang secara tegas melarang rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif negara.
Salah satunya adalah Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara maupun swasta.
“Pasal ini sangat jelas dan tidak multitafsir. Karena wakil menteri merupakan bagian dari struktur kementerian dan pembantu presiden, maka ia semestinya juga terikat pada semangat dan norma yang termuat dalam undang-undang ini,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga mengutip Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang melarang pelaksana pelayanan publik dari instansi pemerintah merangkap jabatan di organisasi usaha.
Di samping itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga dengan tegas melarang adanya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hardjuno turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mempertegas larangan rangkap jabatan bagi menteri.
Menurutnya, putusan tersebut menegaskan bahwa semangat konstitusi Indonesia tidak pernah membenarkan penumpukan kekuasaan administratif dan korporatif dalam satu tangan.
Ia juga membandingkan situasi di Indonesia dengan praktik tata kelola di negara-negara yang lebih maju. Di Prancis, sejak 2014 telah diterapkan aturan ketat yang melarang pejabat publik merangkap jabatan — dikenal dengan istilah cumul des mandats.
Pejabat parlemen di negara tersebut dilarang menjabat di lembaga eksekutif atau pemerintahan daerah demi menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan.
Lebih jauh, Hardjuno mencontohkan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia yang justru menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi tata kelola pemerintahan.
Vietnam mulai membatasi rangkap jabatan setelah terungkapnya berbagai kasus korupsi. Sementara Malaysia, belajar dari skandal besar 1MDB, mulai 2023 melarang menteri merangkap jabatan sebagai ketua BUMN.
“Kalau Vietnam dan Malaysia bisa belajar dari masa lalu, kenapa Indonesia justru mengulang kesalahan yang sama? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab pemerintah,” katanya.
Bagi Hardjuno, persoalan rangkap jabatan bukan sekadar soal regulasi, tetapi menyentuh esensi dari integritas dalam pemerintahan.
Jabatan publik, tegasnya, adalah amanah rakyat — bukan ruang untuk menumpuk kekuasaan dan fasilitas oleh segelintir elite.
“Negara ini tidak kekurangan orang cakap. Tapi bila jabatan publik justru dijadikan alat untuk mengakumulasi kekuasaan, maka kita sedang melenceng jauh dari arah republik yang beretika dan demokratis,” pungkas Hardjuno.