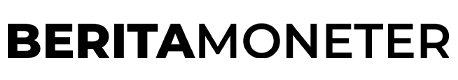Padahal, berbagai laporan, baik dari BPS maupun UNICEF, secara konsisten menunjukkan persoalan pendidikan di wilayah seperti NTT berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, keterbatasan akses, distribusi anggaran yang timpang, serta minimnya layanan pendampingan sosial dan psikologis bagi anak-anak rentan.
Di sinilah politik pencitraan menjadi berbahaya. Ia menciptakan ilusi penyelesaian, padahal yang terjadi hanyalah penundaan krisis. Publik dibuat merasa bahwa negara telah hadir, sementara negara sesungguhnya hanya mampir sebentar. Tragedi kemanusiaan yang seharusnya menjadi alarm kebijakan justru berubah menjadi latar dramaturgi kekuasaan.
Guy Debord, dalam The Society of the Spectacle (1967), menyebut kondisi ini sebagai masyarakat tontonan, di mana realitas digantikan oleh representasi, dan tindakan nyata dikalahkan oleh citra.
Dalam masyarakat semacam ini, yang dinilai bukan lagi seberapa dalam masalah diselesaikan, melainkan seberapa meyakinkan masalah itu ditampilkan di ruang publik. Politik pencitraan bekerja persis dalam logika ini: penderitaan dipertontonkan, empati diproduksi, dan kritik diredam.
Lebih jauh, praktik semacam ini juga melanggengkan relasi kuasa yang timpang. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa simbol, termasuk kepedulian dapat berfungsi sebagai modal untuk mempertahankan dominasi.