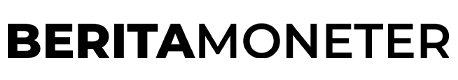Bantuan yang diberikan tidak pernah netral. Sebaliknya, ia membangun relasi “pemberi” dan “penerima”, di mana pihak penerima secara tidak sadar ditempatkan dalam posisi berhutang budi. Inilah yang sebelumnya telah disinggung Derrida sebagai le don impossible, yakni pemberian yang tampak tulus, tetapi menyimpan tuntutan pengakuan.
Ketika politik pencitraan dibiarkan, masyarakat perlahan kehilangan keberanian untuk menuntut hak. Kritik dianggap tidak tahu diri, tuntutan struktural dicap sebagai sikap tidak bersyukur. Dalam jangka panjang, standar kepemimpinan pun merosot. Pemimpin dinilai cukup dengan hadir saat tragedi, bukan dengan mencegah tragedi itu berulang.
Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah empati reaktif, melainkan keberpihakan yang terlembaga dalam kebijakan. Tragedi seperti kematian YBS seharusnya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dasar, pendataan keluarga miskin ekstrem, layanan kesehatan mental anak, serta kehadiran negara di wilayah-wilayah pinggiran. Tanpa itu semua, bantuan apa pun hanya akan menjadi kosmetik sosial. Ia menutup luka di permukaan, sementara infeksi di dalam terus dibiarkan.
Pada akhirnya, publik dituntut untuk lebih waspada. Jangan lagi terpesona oleh gestur sesaat yang ramai diberitakan, tetapi miskin perubahan. Sebab di balik politik pencitraan, tragedi kemanusiaan direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan, sementara penderitaan yang sesungguhnya tetap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.*