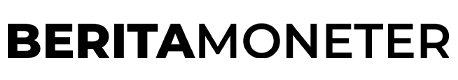Merujuk pada uraian fenomena di atas, muncul pertanyaan kritis, dalam bentuk apa tanggung jawab moral yang mungkin mereka lakukan? Sebagai ksatria, ada satu hal yang bia dilakukan dari dua pilihan, yaitu “move on” atau mundur dari pegawai KPK.
Tindakan move on, yaitu dari menolak menjadi “orang tertunduk” yang disertai dengan dua “derita” sekaligus.
Derita Pertama, “kehilangan muka”. Mereka amat sulit menegakkan kepalanya ketika “berinteraksi” dengan sesama karyawan, apalagi berhadapan dengan lima pimpinan KPK yang baru.
Bahkan yang paling “menyiksa” perasaan mereka, ke depan pegawai tersebut sudah tidak bisa “tegak” dan lantang berbicara di ruang publik secara terbuka, seperti mereka lakukan ketika mewacanakan penolakan terhadap capim KPK.
Derita pertama tadi sekaligus mengantar mereka masuk pada derita berikutnya.
Derita kedua. Ibarat masuk ke kandang harimau, kemuadian lanjut masuk ke kandang buaya. Derita kedua, menjadi “pekerja patuh”.
Dengan derita ini, posisi tawar mereka terhadap pimpinan KPK dan kepada sesama karyawan yang selama ini tidak menolak capim KPK yang baru, dipastikan sangat-sangat rendah.
Mereka seperti ayam jago kehilangan taji, atau ibarat singa ompong. Sudah sulit bagi mereka bersuara nyaring. Mereka seolah sudah “menyumbat” mulutnya sendiri.